Model
pengolahan sampah di Indonesia ada dua macam, yaitu urugan dan
tumpukan. Model pertama merupakan cara yang paling sederhana, yaitu
sampah dibuang di lembah atau cekungan tanpa memberikan perlakuan.
Urugan atau model buang dan pergi ini bisa saja dilakukan pada lokasi
yang tepat, yaitu bila tidak ada pemukiman di bawahnya, tidak
menimbulkan polusi udara, polusi pada air sungai, longsor, atau
estetika. Model ini umumnya dilakukan untuk suatu kota yang volume
sampahnya tidak begitu besar.
Pengolahan
sampah yang kedua lebih maju dari cara urugan, yaitu tumpukan. Model
ini bila dilaksanakan secara lengkap sebenarnya sama dengan teknologi
aerobik. Hanya saja tumpukan perlu dilengkapi dengan unit saluran air
buangan, pengolahan air buangan (leachate), dan pembakaran ekses gas metan (flare). Model
yang lengkap ini telah memenuhi prasyarat kesehatan lingkungan. Model
seperti ini banyak diterapkan di kota-kota besar. Namun, sayangnya
model tumpukan ini umumnya tidak lengkap, tergantung dari kondisi
keuangan dan kepedulian pejabat daerah setempat akan kesehatan
lingkungan dan masyarakat. Aplikasinya ada yang terbatas pada tumpukan
saja atau tumpukan yang dilengkapi saluran air buangan, jarang yang
membangun unit pengolah air buangan. Meskipun demikian, ada suatu
daerah yang mengelolanya dengan kreatif. Berikut ini beberapa model
pengolahan sampah di beberapa kota di Jawa.
1. DKI Jakarta (Bantar Gebang)
Pengolahan
sampah DKI Jakarta di Bantar Gebang telah didirikan sejak tahun 1986.
Lokasi lahan di Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI
Jakarta membayar tipping fee kepada Pemda Bekasi sebesar Rp
60 juta per ton sampah. TPA Bantar Gebang dikelola dengan penerapan
sistem tumpukan yang dilengkapi dengan IPAS (Instalasi Pengolahan Air
Sampah) dan sistem drainage. Sistem drainage ini untuk menampung air buangan atau lindi hitam (leachate) ke dalam IPAS dan membuangnya ke sungai terdekat.
Sistem IPAS menggunakan activated sludge system, yaitu danau yang diberi aerasi dengan agitator (pengaduk
bertenaga besar). Operasional IPAS dan kebersihan drainage perlu
dikontrol dengan baik setiap hari agar tidak terjadi klaim dari
masyarakat tentang kualitas air buangan. Demikian juga jalan yang
dilalui truk perlu dijaga kebersihan dari tetesan air yang keluar dari
truk dan sampah yang berserakan sepanjang jalan tersebut. Tujuannya
agar terhindar dari bau, pemandangan yang tidak sedap, serta munculnya
penyakit yang berhubungan dengan kesehatan kulit dan paru-paru. Namun,
pada kenyataannya, pada tahun 2005 penduduk di sekitar TPA terserang
penyakit dermatitis sebanyak 2.710 orang.
Pembakaran
gas metan juga dilakukan pada beberapa timbunan meskipun tidak tertata
baik. Pemisahan material anorganik dilakukan oleh pemulung yang
jumlahnya puluhan orang serta sudah merupakan kegiatan sosial-ekonomi
tersendiri dan melibatkan bisnis yang nilainya cukup besar. Meskipun
model ini sangat minimal, tetapi terbukti efektif dan telah menolong
masyarakat DKI Jakarta dalam mengatasi masalah sampah.
Permasalahan
sampah di DKI Jakarta saat ini adalah volume sampah yang sudah tidak
bisa ditampung lagi oleh areal yang ada. Perluasan areal ke daerah
lain, terutama lintas provinsi tidak akan memecahkan persoalan, tetapi
hanya akan memindahkan persoalan. Dengan pendekatan ilmiah diharapkan
akan ada jalan keluar yang lebih arif dan efektif.
2. Surabaya (Sukolilo)
Model
TPA di Surabaya persis sama dengan DKI Jakarta. Sekitar tahun 1980-an
TPA Sukolilo diprotes oleh masyarakat setempat karena menimbulkan
polusi bau, padahal masyarakat datang ke lokasi setelah TPA tersebut
berjalan beberapa tahun. Namun, hal ini tidak bisa diabaikan karena
masalah sosial bagian dari masalah sampah kota. Sebagai jalan keluar,
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya selanjutnya mengimpor 1 (satu) unit incinerator (pembakar)
sampah dari Inggris. Ternyata, alat tersebut tidak efektif karena biaya
pembakaran sangat besar dan polusi bau berubah menjadi asap dan debu,
bahkan partikulat.
Aplikasi incinerator di
Indonesia kurang sesuai karena kadar air sampah sangat tinggi (>80%)
sehingga sebagian besar energi yang digunakan untuk membakar (minyak
residu) adalah untuk menguapkan air. Hal tersebut mengakibatkan biaya
operasional alat tersebut menjadi sangat tinggi. Solusinya adalah TPA
dipindahkan lokasinya ke daerah pantai di wilayah kabupaten Sidoardjo.
Masalah yang mungkin timbul di TPA baru ini adalah salinitas yang bisa
menghambat efektivitas kerja mikroba. Selain itu, air buangan (leachate) dari
sampah akan mengotori perairan/perikanan karena jaraknya yang terlalu
dekat. Semua kelemahan tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan
pendekatan teknologi asal memungkinkan biayanya. Aplikasi incinerator di Indonesia kurang sesuai karena kadar air sampah sangat tinggi.
3. Solo (Mojosongo)
Pengolahan
sampah di Kota Solo perlu dibahas secara khusus karena cukup menarik.
Model pengolahan adalah cara tumpukan seperti di daerah lain.
Kelebihannya adalah sampah pada gundukan yang telah menjadi kompos
dibagi-bagikan secara gratis kepada masyarakat. Masyarakat menyaring
kompos dari bahan organik yang tidak terurai serta kotoran kasar,
kemudian dijual. Dengan cara ini ada sistem input dan sistem output sehingga luasan areal TPA untuk timbunan sampah akan lebih lama penuh karena output berupa kompos selalu keluar dari areal tersebut.
Masyarakat
sekitar juga diuntungkan karena adanya penghasilan tambahan yang cukup
besar. Selain itu, sistem tersebut berhasil memacu tumbuh-kembangnya
pertanian organik di wilayah tersebut. Hal lain yang menarik adalah
adanya hewan ternak sapi yang dipelihara oleh penduduk sekitar dengan
cara dilepas secara liar di areal TPA untuk mencari makanan sendiri.
Sapi-sapi ini pada pagi hari keluar sendiri dan pada waktu magrib masuk
kembali ke kandangnya masing-masing. Berdasarkan penelitian dari WHO,
temyata susu, tidak tercemar oleh kotoran yang berasal dari sampah.
Jumlah sapi pada tahun 1995 mencapai 1.000 ekor. Sapi tersebut
menghasilkan susu dan daging bagi penduduk sekitar yang tadinya adalah
para pemulung.
Pada
awal pembangunan TPA, penduduk yang tinggal di pinggir sebelah kiri dan
kanan jalan menuju TPA adalah pemulung yang diimpor dari daerah lain.
Pemulung tersebut diberikan gubuk sederhana (settlement) oleh
pemda setempat. Kini gubuk-gubuk tersebut telah berubah menjadi rumah
bata dan hampir setiap rumah memiliki motor. Anak-anaknya pun
disekolahkan di perguruan tinggi. Setiap pagi hari, berpuluh-puluh truk
parkir di sepanjang jalan menuju TPA melakukan transaksi bisnis
jual-beli material selain sampah, seperti kertas/karton, besi, plastik,
kaleng, dan aluminium. Model ini ternyata bisa dijadikan contoh cara
pengelolaan sampah yang berhasil karena terasa manfaatnya bagi
masyarakat tingkat rendah, di samping juga dapat mengatasi masalah
lingkungan.
4. Daerah lainnya
Di
beberapa kota di Jawa Barat yang penduduknya tidak begitu padat dan
memiliki topografi lembah dan pegunungan seperti di Kota Kuningan,
Sumedang, Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya, sampahnya dibuang ke lembah.
Cara tersebut juga dianut pada kota lainya di Jawa Tengah dan Jawa
Timur karena cukup efektif dan murah.
Di
Jogyakarta, pengolahan sampah dilakukan dengan cara tumpukan dan
dilengkapi dengan unit pengolahan sampah masinal (mesin) yang dikelola
oleh pemda setempat. Cara tumpukan telah dilakukan secara profesional.
Di Malang, TPA cara tumpukan dibangun dengan bantuan dana asing dan
dirancang secara modern dengan mengambil lokasi di suatu lembah. Di
Bogor, terutama TPA di daerah Gunung Galuga, Leuwiliang, juga
menggunakan cara tumpukan, tetapi karena tingginya curah hujan maka
sampah kota memerlukan waktu cukup lama untuk pembusukannya. Model incinerator yang
diimpor dari Perancis pernah dicoba, tetapi akhimya kembali gagal
seperti di Surabaya. Di Bandung kasusnya sama dengan DKI Jakarta, yaitu
kemampuan TPA di daerah Lembang sudah tidak bisa mengatasi volume
sampah yang begitu besar, di samping cuaca yang sangat dingin sehingga
pembusukan berjalan sangat lambat.


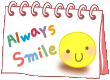
0 komentar:
Posting Komentar